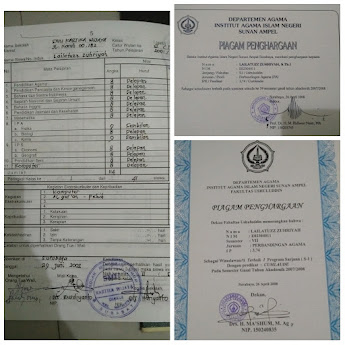Suatu sore yang cerah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tidak biasanya sore ini terasa begitu panas. Pasalnya, beberapa hari ini, di Tulungagung selalu hujan di sore hari. Sore ini (Selasa, 20 Mei 2025), saya memasuki ruang kelas PGMI 2-D untuk mengajar mata kuliah Filsafat Umum. Meski hari sudah sore — setelah mengikuti kegiatan upacara, menguji skripsi, menyeleksi administrasi proposal penelitian dari para dosen di aplikasi Litapdimas — mengajar harus tetap semangat.
Sore ini, saya mengajak mahasiswa menyelami pemikiran salah satu filsuf besar Eropa: Immanuel Kant. Materi hari ini adalah tentang Kritisisme Immanuel Kant, sebuah materi yang kerap dianggap sulit, rumit, bahkan cenderung membingungkan bagi mahasiswa semester awal di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Namun, justru di dalam kerumitan itulah saya ingin menantang diri saya dan mahasiswa, "mari berpikir lebih dalam".
Seperti biasa, saya memulai perkuliahan dengan mengajak mahasiswa mengingat materi sebelumnya, dan mencoba menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Dalam mengajar Filsafat, saya kerap kali menggunakan pendekatan contextual teaching and learning (CTL), pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengaitan materi kuliah dengan konteks kehidupan nyata para mahasiswa. Tujuannya? tentu saja agar mereka lebih memahami materi filsafat, yang konon ditakuti mahasiswa FTIK. Selain takut karena sulit, juga takut menjadi kafir. He... he....
Dalam pembahasan materi tentang Kritisisme Immanuel Kant hari ini, ada salah satu sub bahasan yang cukup menarik, yakni Etika Immanuel Kant tentang "kehendak baik". Kant membedakan kehendak baik dalam dua jenis, yakni: legalitas dan moralitas. Secara sederhana, saya menjelaskan bahwa legalitas itu lebih mengarah kepada suatu tindakan baik yang dilakukan seseorang karena memiliki motif tertentu, yakni berbuat baik karena ada aturan yang mengatur tentang itu, atau ada sanksi jika tidak mengindahkan. Namun, hal ini berbeda dengan moralitas. Moralitas itu secara sederhana adalah berbuat baik karena memang ada dorongan dalam diri, semacam kesadaran bagi diri untuk berbuat kebaikan bukan karena embel-embel tertentu.
Saya mencoba menjelaskan dengan hati-hati, dan pelan-pelan, agar mereka bisa memahami. Tak lupa, metode tanya jawab juga menjadi metode yang wajib guna mengembangkan nalar kritis mereka, sebagaimana tuntutan pembelajaran abad 21. Saya rasa, dengan mengajak mereka bernalar kritis, dan berfikir reflektif, akan membuat mereka bisa memahami filsafat, sekaligus mengambil pelajaran baik yang ada di dalamnya untuk diterapkan dalam hidup.
Antara Takut Denda dan Kesadaran Ekologis
Untuk membuat mahasiswa lebih memahami, saya memberikan satu contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni terkait dengan membuang sampah.
Bayangkan, kita sedang berjalan di tepi sungai. Di situ terpampang jelas papan bertuliskan: “Dilarang membuang sampah di sungai. Denda Rp 1000.000.” Lalu kita pun menahan diri untuk tidak melempar sampah ke sungai. Apakah itu tindakan baik? Ya. Tapi, apakah tindakan itu mencerminkan moralitas? Belum tentu.
Menurut Kant, tindakan tersebut mencerminkan legalitas. Artinya, kita berbuat baik hanya karena ada hukum eksternal, ada imbalan atau ancaman. Kita melakukan sesuatu yang baik dengan tidak membuang sampah karena takut denda. Motifnya bukan karena sadar akan pentingnya menjaga ekosistem sungai, akan tetapi karena ingin menghindari hukuman.
Sebaliknya, jika seseorang tidak membuang sampah ke sungai tanpa perlu adanya himbauan atau denda, tetapi karena ia merasa bahwa lingkungan itu harus dijaga, sungai adalah sumber kehidupan, dan bumi adalah amanah Tuhan—maka itulah yang disebut moralitas. Tindakan tersebut berasal dari kesadaran internal, bukan dari tekanan eksternal.
Beribadah karena Takut atau karena Cinta?
Setelah menjelaskan perbedaan legalitas dan moralitas, saya lalu mengajak mahasiswa merenung lebih jauh. Saya katakan kepada mereka bahwa konsep ini bisa juga kita bawa ke dalam praktik keagamaan kita.
Kita sebagai seorang Muslim, menjalankan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, membaca Al-Qur’an. Tapi, apa motif kita di balik semua itu?
Kerap kali, tanpa sadar, kita beribadah karena motif legalitas: karena takut dosa, takut neraka, ingin pahala, ingin surga. Ada janji dan ancaman. Ada hukum syariat yang mengatur. Apakah hal itu salah? Barangkali, ini wajar dan sering kita alami. Kita kerap kali menjalankan sesuatu yang baik karena ada embel-embel tertentu. Tapi, Kant mungkin akan bertanya, "apakah hal yang seperti itu benar-benar tindakan moral?"
Saya lalu menyampaikan gagasan ini kepada mahasiswa, "bagaimana kalau kita mencoba memaknai ibadah sebagai ekspresi dari kesadaran eksistensial? Kita beribadah bukan karena takut, bukan karena imbalan, tetapi karena kita mencintai Tuhan, karena kita merasa kecil dan bersyukur sebagai hamba-Nya, karena kita menyadari bahwa ibadah adalah cara kita menjaga hubungan dengan yang Transenden."
Inilah yang disebut "moralitas spiritual", yakni beribadah karena dorongan nurani, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, kita tidak membuang sampah bukan karena takut didenda, tapi karena kita mencintai bumi. Begitu juga kita beribadah bukan karena takut siksa, tapi karena kita mencintai Tuhan.
Etika Kant: Jalan Menuju Otonomi Moral
Mengapa Immanuel Kant begitu menekankan pentingnya kehendak baik? Hal ini karena bagi Kant, hanya tindakan yang didorong oleh imperatif kategoris lah—yaitu prinsip moral yang berlaku secara universal dan lahir dari rasio murni manusia—yang bisa disebut sebagai tindakan yang benar-benar bermoral.
Imperatif kategoris Kant ini memiliki bentuk klasik, “Bertindaklah sedemikian rupa seolah-olah maksim dari tindakanmu dapat menjadi hukum universal.” Maknanya, kita harus bertindak dengan cara yang jika diuniversalkan, akan tetap benar dan pantas.
Misalnya, jika saya berpikir bahwa mencuri itu bisa dibenarkan saat saya butuh, maka saya juga harus bisa menerima juga tatkala suatu saat nanti semua orang juga akan mencuri saat mereka butuh. Jika hal ini terjadi, maka tidak akan ada lagi konsep tentang "milik pribadi". Oleh karena itu, mencuri menjadi tidak bisa diterima secara universal, dan karenanya dianggap tidak bermoral.
Kant menyebut orang yang mampu bertindak baik berdasarkan pada imperatif kategoris ini adalah sebagai orang yang memiliki "otonomi moral". Maknanya, dia tidak akan bisa dikendalikan oleh hukum luar, melainkan dia hanya bisa dikendalikan oleh hukum moral yang ada di dalam dirinya. Ia bertindak bukan karena takut atau karena diiming-imingi, tetapi karena ia sadar bahwa itu adalah hal yang benar.
Menjadi Manusia Bermoral di Era Hukum dan Sanksi
Saat ini, hampir setiap aspek kehidupan kita diatur oleh regulasi, undang-undang, kode etik, bahkan sanksi sosial. Semua itu memang sangat penting dan perlu. Tanpa aturan, maka akan terjadi kekacauan. Namun, jika kita merefleksi konsep yang ada pada etika Kant, sejatinya kita sedang diajak untuk melangkah lebih jauh, yakni "bisakah kita tetap bertindak baik meski tidak ada kamera CCTV, tidak ada denda, tidak ada pahala?"
Inilah tantangan moralitas yang sejati.
Saya membayangkan, Kant seolah-olah berkata, "jangan hanya jadi manusia legal, jadilah manusia moral. Jangan hanya takut aturan, tapi tumbuhkan kesadaran etis. Jangan hanya berbuat baik karena dilihat orang, tapi berbuat baiklah karena kamu tahu bahwa itu adalah yang benar".
Refleksi Pendidikan: Dari Kepatuhan ke Kesadaran
Sebagai pendidik, saya merasa terpanggil untuk membawa semangat ini ke dalam ruang-ruang kelas. Bagi saya, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi lebih pada sebuah proses transformasi kesadaran. Kita bukan hanya ingin mencetak mahasiswa yang taat aturan, tapi mahasiswa yang berkesadaran etis.
Oleh karena itu, saat kita mengajarkan pendidikan lingkungan kepada mereka, jangan hanya menanamkan mindset kepada mereka bahwa buang sampah sembarangan bisa kena denda. Tetapi, ajarkan pula bahwa bumi ini adalah titipan, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan.
Begitu juga saat kita mengajarkan pendidikan agama kepada mereka, jangan hanya menekankan soal pahala dan siksa saja. Tetapi, ajarkan juga bahwa beribadah adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Bahwa menjadi manusia yang baik, bukan karena demi surga, tetapi karena itulah hakikat menjadi manusia yang sejati.
Menuju Spiritualitas Otonom
Sebenarnya, jika dianalisis, terdapat irisan antara spiritualitas Islam dengan etika Kant. Dalam tasawuf misalnya, kita mengenal konsep maqamat atau tingkatan-tingkatan ruhani. Salah satu tingkatannya adalah mahabbah, yakni cinta kepada Tuhan.
Sebagaimana diketahui bahwa para sufi beribadah bukan karena takut akan neraka atau menginginkan surga. Tetapi karena mereka mencintai Tuhan. Mereka berkata, “Andaikan tidak ada neraka atau surga, kami tetap beribadah karena kami mencintai-Mu.”
Bukankah hal yang demikian ini sejalan dengan konsep moralitas Immanuel Kant? Bahwa tindakan baik yang sejati adalah yang lahir dari niat yang murni dan kesadaran batin.
Maka, dari sinilah mungkin kita bisa menemukan sebuah titik temu, antara filsafat Barat dengan spiritualitas Timur, antara Kant dengan Rabi’ah al-Adawiyah, dan antara reason dengan love. Bukan begitu?
Mendidik Nurani, Menemukan Kemanusiaan
Perkuliahan sore ini ditutup dengan refleksi tentang konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Perkuliahan sore ini tak lagi bicara soal Kant sebagai sekedar seorang filsuf Eropa abad ke-18. Tetapi menyadari bahwa sejatinya filsafat bukan sekedar teori abstrak, melainkan cermin untuk memahami kehidupan sehari-hari, bahkan ibadah kita.
Saya meyakini bahwa pendidikan akan berhasil bukan ketika mahasiswa bisa menghafal definisi dari “imperatif kategoris,” tetapi ketika mereka bisa berkata: “Saya tidak buang sampah karena saya mencintai bumi. Saya shalat bukan karena takut neraka, tapi karena saya mencintai Tuhan.”
Jika hal ini tercapai, maka saya yakin bahwa kita sudah mendekati apa yang disebut Kant sebagai "manusia bermoral", dan dalam bahasa kita disebut sebagai "manusia yang bertakwa adalah bukan karena takut, tapi karena cinta." 😊